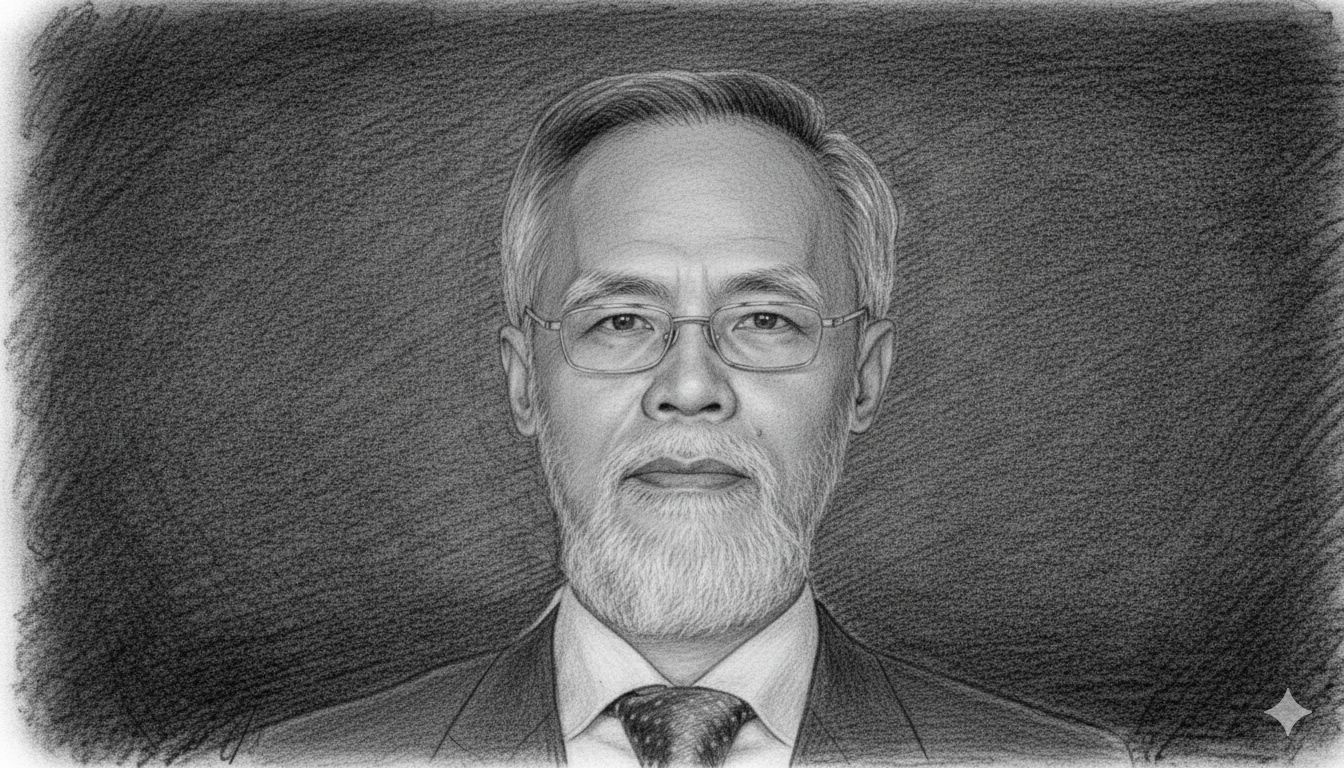Oleh: Ahmad Fauzan
Partisipasi politik dapat dipahami sebagai komitmen masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik yang berkelanjutan, tidak sekedar mencoblos saat pemilu. Sebagaimana dijelaskan Prof. Miriam Budiardjo dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, secara umum partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam memilih pemimpin dan mempengaruhi suatu kebijakan.
Pada era digital sekarang ini, platform media sosial seperti TikTok dan Instagram menjadi alternatif bagi masyarakat terutama generasi muda untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan membangun solidaritas sosial. Tuntutan 17+8 adalah contoh nyata bahwa aktivisme digital mampu menarik perhatian publik dan memperoleh banyak dukungan. Namun, keterlibatan aktif di media sosial menimbulkan tanda tanya besar, apakah partisipasi politik digital akan menjadi solusi demokrasi atau hanya ilusi keterlibatan?
Berdasarkan DataReportal Indonesia 2025, platform TikTok tercatat memiliki 108 juta pengguna, disusul oleh Instagram dengan 103 juta pengguna. Data tersebut memberikan jawaban kenapa fenomena aktivisme digital di media sosial seperti TikTok dan Instagram memperoleh banyak dukungan, karena tidak sedikit penduduk Indonesia yang menggunakan kedua platform media sosial tersebut untuk mendapatkan informasi terbaru.
Mereka menyoroti isu-isu nasional seperti tunjangan DPR RI yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu sehingga memicu respons negatif dari berbagai kalangan. Bentuk aktivisme digital yang paling sering muncul yaitu “clicktivism” tindakannya berupa menyukai, membagikan, menggunakan tagar tertentu, menandatangani petisi digital, dan mengganti foto profil dengan tema tertentu sebagai bentuk solidaritas.
Gerakan tersebut mempermudah masyarakat untuk berkontribusi tanpa harus turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, namun gerakan tersebut sering kali terhenti karena tidak memiliki arah pergerakan yang jelas. Foto profil dengan tema hijau dan pink adalah bukti nyata bahwa gerakan tersebut lebih terkesan ekspresi simbolis karena tidak diiringi dengan aksi nyata yang berdampak pada kebijakan.
Di sisi lain, aktivisme digital juga memiliki keterbatasan akses ke institusi formal yang berwenang dalam pengambilan keputusan, sehingga tuntutan masyarakat sering kali tidak terakomodasi dalam proses legislasi. Jadi meskipun partisipasi masyarakat meningkat melalui “clicktivism”, kualitas dan keberlanjutannya dipertanyakan.
David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam buku The Comparative study of politics (1976) menjelaskan piramida partisipai politik yang terbagi menjadi empat tingkatan yaitu aktivis, partisipan, penonton, apolitis. Jika dilihat dari piramida tersebut, gerakan “clicktivism” dapat dikategorikan sebagai penonton karena “clicktivism” terbatas di ruang digital saja tanpa melakukan aksi nyata yang berdampak terhadap kebijakan.
Banyak dari mereka yang mudah dimobilisasi karena termakan oleh hoaks atau hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui makna dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga partisipasi yang ada tergolong pasif. Berbeda dengan partisipan yang aktif melakukan tindakan-tindakan politis seperti menjadi anggota partai tertentu. Jika “clicktivism” ingin dikategorikan partisipasi aktif, maka tindakan di ruang digital harus diiringi dengan aksi nyata, misalnya diskusi secara langsung dengan membentuk komunitas sehingga “clicktivism” tidak terhenti di media sosial yang minim komitmen jangka panjang.
Fenomena aktivisme digital seperti “clicktivism” memang meningkatkan angka partisipasi masyarakat, dapat dilihat akhir-akhir ini semakin banyak pengguna
TikTok dan Instagram yang menyuarakan isu-isu keadilan dan kebebasan. Namun, kualitas dan keberlanjutannya bisa dikatakan rendah karena menyukai, membagikan, penggunaan tagar, menandatangani petisi digital, mengganti foto profil dengan tema tertentu bisa dilakukan tanpa komitmen, dan banyak yang sekedar ikut-ikutan agar terlihat keren dimata publik.
Di sisi lain, keberadaan buzzer dan hoaks yang merajalela di media sosial berpotensi memecah-belah masyarakat menjadi dua kubu yang saling berlawanan, hal tersebut akan memicu terjadinya konflik baru di media sosial. Sebagai masyarakat kita perlu jeli dalam menerima informasi agar tidak mudah dimobilisasi oleh buzzer dan termakan oleh hoaks. Algoritma dan mekanisme iklan sering kali lebih menguntungkan influencer yang memiliki banyak pengikut dan modal, sehingga kualitas argumen yang muncul di beranda cenderung dangkal. Dengan demikian “clicktivism” bagaikan pisau bermata dua, bisa digunakan untuk kepentingan sosial tetapi juga rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Partisipasi politik digital sebagai alternatif bagi generasi muda berpotensi menjadi solusi demokrasi jika diiringi dengan aksi nyata, sehingga mampu menutup ilusi keterlibatan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan seperti budaya ikut-ikutan, keberadaan buzzer dan hoaks, serta media sosial yang tidak netral.
Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menutup ilusi keterlibatan pertama, pengembangan platform digital sebagai wadah partisipasi digital seperti layanan pengaduan yang baru-baru ini dibuat oleh Menkeu Purbaya. Kedua, mengadakan program edukasi digital terutama bagi kalangan muda, misalnya edukasi tentang cara membedakan fakta dengan hoaks dan etika dalam media sosial.
Ketiga, adanya regulasi yang jelas dan transparan dalam mengatur algoritma dan mekanisme iklan agar netralitas media sosial terjamin. Keempat, mewajibkan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menyediakan fitur pelaporan informasi palsu. Kelima, penyatuan diskusi digital dengan diskusi langsung sehingga aktivisme digital dapat menjadi langkah awal terwujudnya aksi nyata. Dengan langkah-langkah tersebut akan mendorong partisipasi politik digital yang lebih berkelanjutan dan akan menghapus ilusi keterlibatan yang masif di platform media sosial. (*)
Ahmad Fauzan, mahasiswa Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas

 3 months ago
67
3 months ago
67