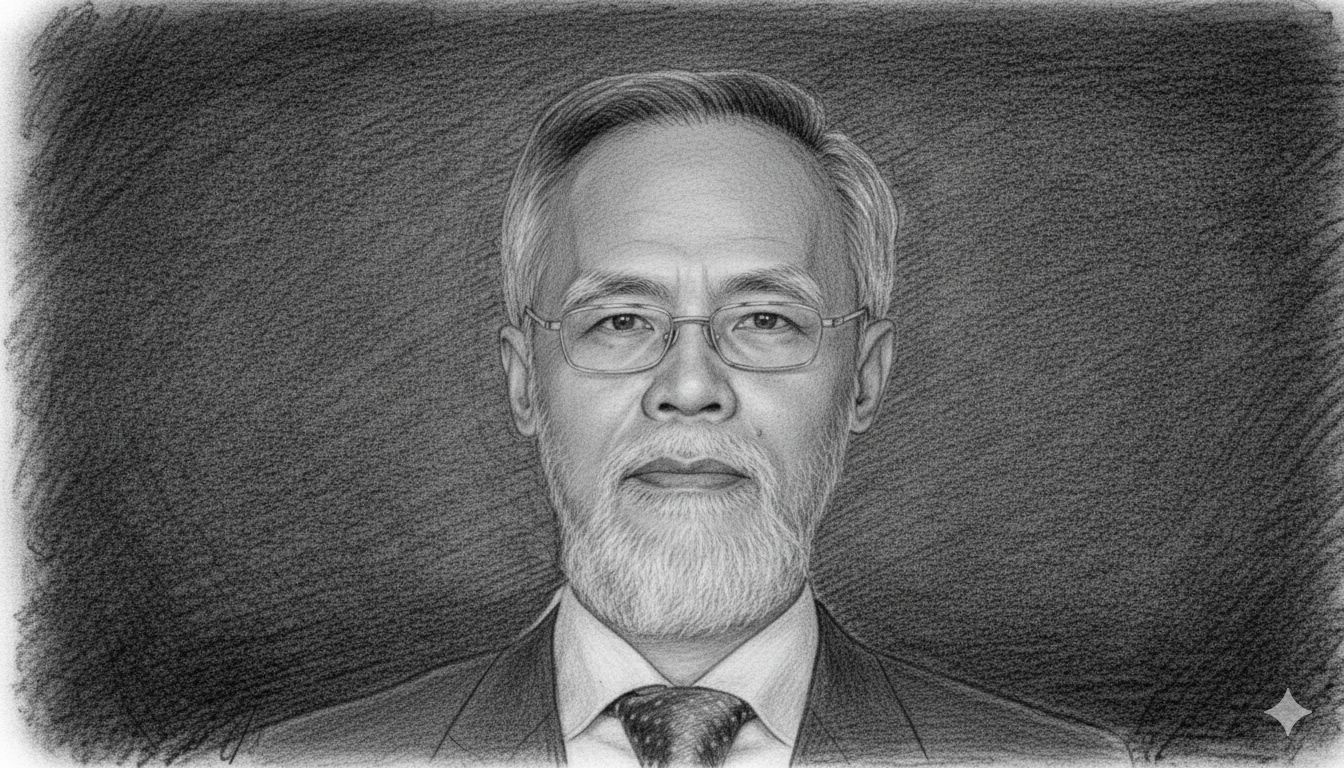Oleh: Tanzilla Wulandari
Fenomena politik uang seolah sudah menjadi wajah yang sulit dihapus dari setiap kontestasi demokrasi di Indonesia. Mulai dari pemilu pilkada, legislatif, bahkan pemilihan presiden, praktik bagi-bagi uang maupun barang masih sering ditemukan. Mirisnya, praktik ini bagi sebagian masyarakat masih dianggap hal yang biasa bahkan sudah menjadi tradisi dalam pemilu. Padahal, praktik ini jelas menodai esensi demokrasi yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, pengalaman, kepemimpinan, malah menjadi transaksi finansial. Seperti yang telah ditegaskan oleh Miriam Budiarjo (2008) demokrasi sejati bukan tentang seberapa sering pemilu diselenggarakan, melainkan sejauh mana rakyat berpartisipasi secara sadar tanpa tekanan dan tanpa iming-iming materi. Oleh karena itu, praktik politik uang ini jelas mencederai makna sejati demokrasi. Lebih dari itu, politik uang juga merupakan pintu masuk utama korupsi. Para kandidat yang membeli suara akan terdorong untuk “mengembalikan modal” yang sudah dikeluarkan selama kampanye. Selama politik uang terus dibiarkan, korupsi tidak akan pernah surut, dan demokrasi hanya akan menjadi topeng semata. Dari sinilah lingkaran setan politik uang dan korupsi lahir: kekuasaan berubah menjadi investasi, bukan pengabdian yang merusak demokrasi dan merugikan masyarakat luas.
Salah satu akar suburnya politik uang adalah tingginya biaya politik di Indonesia. Untuk menjadi calon pejabat, seseorang harus mengeluarkan biaya politik yang sangat besar mulai dari kampanye, konsolidasi tim, hingga “ongkos politik” yang bersifat tidak resmi. Di sinilah politik uang lahir dan mendapatkan ruang. Uang tunai, sembako, bahkan janji-janji fasilitas diberikan untuk membeli suara. Dengan biaya yang mahal timbul masalah besar yang kurang diperhatikan.
Masalahnya ketika kandidat terpilih, modal yang dikeluarkan pasca pemilihan harus dikeluarkan. Gaji satu periode sering kali tak cukup menutup modal yang sudah dikeluarkan sebelumnya, apalagi dengan sifat alamiah manusia balik modal saja tidak cukup apalagi rugi. Maka muncul dorongan bahkan keinginan untuk menggunakan cara yang lebih cepat demi mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Said Salahudin (2014) menyebut politik uang sebagai bentuk nyata dari korupsi elektoral, sebab praktik ini menggerogoti legitimasi demokrasi, suara rakyat tidak lagi diperoleh melalui keyakinan politik, melainkan hasil transaksi uang. Hasilnya bisa ditebak : mulai dari praktik suap, penyalahgunaan anggaran bahkan jual beli kebijakan. Kursi kekuasaan bukan lagi menjadi alat transportasi gagasan melainkan menjadi ladang investasi.
Politik uang melahirkan lingkaran setan yang menggerus kualitas demokrasi. Pertama, masyarakat yang menerima menjadi permisif terhadap perilaku koruptif pejabat, karena merasa legitimasi untuk menuntut telah hilang. Kedua, pejabat publik merasa memiliki justifikasi moral untuk korupsi, sebab kursinya diperoleh melalui mekanisme transaksi. Ketiga, demokrasi mengalami erosi legitimasi karena pemilu hanya menjadi arena transaksional, bukan kontestasi gagasan.
Kondisi ini menggeser demokrasi dari substansi menuju formalitas. Pemilu sekedar prosedur lima tahunan tanpa kualitas deliberasi (pertimbangan bersama). Rakyat mulai kehilangan peran sebagai pemilik kedaulatan, sementara elite politik memposisikan diri sebagai aktor dominan yang memperjualbelikan kekuasaan.
Dampak politik uang ini sangat luar biasa, mulai dari rendahnya kualitas kepemimpinan di mana kandidat dengan integritas dan kapasitas seringkali tersingkir karena keterbatasan modal. Sebaliknya, kandidat dengan finansial yang tinggi lebih berpeluang menang, walaupun lemah dalam visi dan kompetensi. Implikasinya, kebijakan publik seringkali lebih diarahkan untuk menguntungkan kelompok pemodal dibanding rakyat. Pembangunan diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu, bukan kesejahteraan bersama. Rakyat hanya jadi objek lima tahunan, sementara pemodal menjadi subjek utama yang dikawal kepentingannya. Praktik patronase semakin menguat, di mana kepentingan rakyat dikorbankan demi menjaga relasi dengan penyandang dana politik. Akibatnya, kualitas kebijakan publik menurun dan seringkali tidak menyentuh masyarakat: mulai pembangunan yang tidak merata, layanan dasar yang sangat penting seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan, dan alokasi anggaran sering dipolitisasi. Demokrasi pun gagal menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Menganggap politik uang sebagai tradisi adalah bentuk kekeliruan yang konseptual. Tradisi adalah sesuatu yang diwariskan karena mengandung unsur kebaikan. Sedangkan politik uang justru sebaliknya, yang merupakan bentuk kejahatan elektoral yang merusak moral politik dan mengancam keberlanjutan demokrasi. Sikap yang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang lumrah sama saja dengan melegitimasi lahirnya pemimpin yang korup. Dengan dalih “mumpung ada yang memberi”, masyarakat sesungguhnya tengah menggadaikan masa depan bangsa demi kepentingan sesaat.
Untuk memutus lingkaran setan politik uang dan korupsi, beberapa langkah strategis diperlukan. Pertama, penegakan hukum yang tegas. Bawaslu dan aparat penegak hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku politik uang, biar jera. Kedua, transparansi biaya kampanye. Publik harus mengetahui sumber dan penggunaan dana politik, sehingga dapat menilai independensi kandidat terhadap kepentingan pemodal. Ketiga, pendidikan politik yang substantif. Partai politik, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa harus aktif membangun kesadaran bahwa suara rakyat adalah mandat, bukan komoditas.
Namun, faktor terpenting tetap berada pada masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menolak uang politik adalah fondasi utama pemberantasan korupsi. Meski tidak mudah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit, sikap menolak merupakan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas demokrasi.
Dengan demikian, politik uang bukan sekadar masalah teknis dalam pemilu, melainkan problem struktural yang memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Selama praktik ini masih dianggap wajar, korupsi akan terus berulang, dan demokrasi kehilangan maknanya. Pandangan ini sejalan dengan Samuel P. Huntington (1991) yang menegaskan bahwa ketika kekuasaan dijadikan alat untuk memperkaya diri, demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa makna. Inilah yang terjadi ketika politik uang dibiarkan tumbuh di setiap kontestasi politik. Demokrasi tidak boleh dikorbankan hanya karena selembar uang. Demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, menolak politik uang adalah prasyarat utama bagi lahirnya kepemimpinan yang bersih, kebijakan publik yang adil, serta demokrasi yang bermartabat. (*)
Tanzilla Wulandari, mahasiswa Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas

 3 months ago
72
3 months ago
72