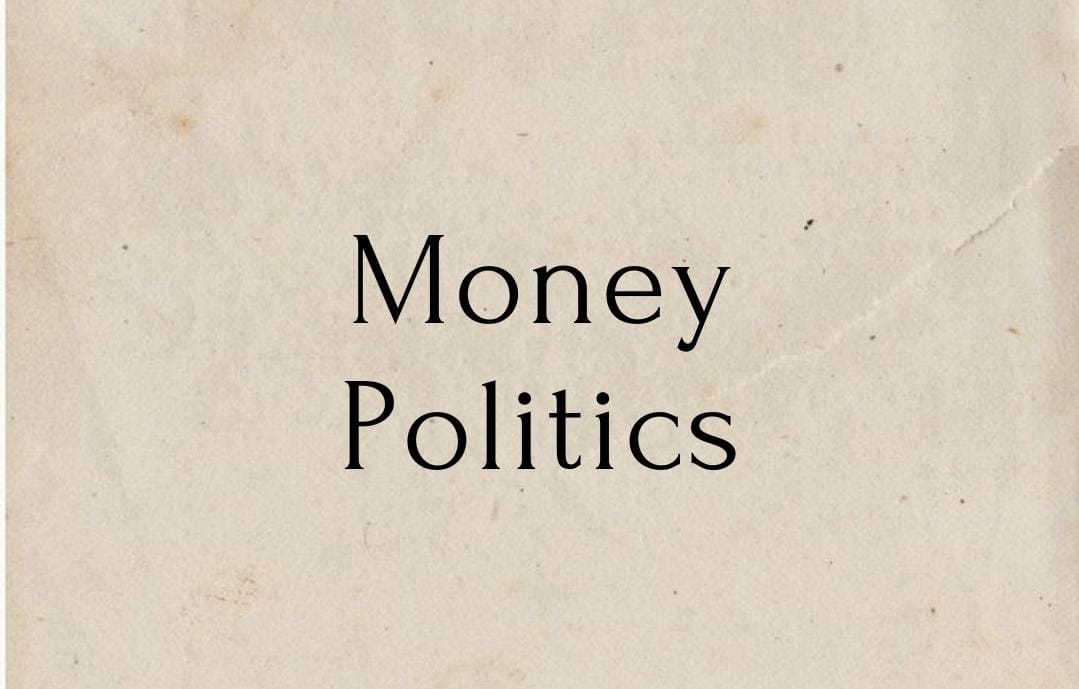Pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengguncang pasar energi dunia. Ia menyatakan akan menerapkan tarif sekunder sebesar 25% hingga 50% terhadap negara mana pun yang membeli minyak dari Rusia—kecuali jika Moskow menyetujui gencatan senjata dalam konflik Ukraina (Shalal, 2025). Ini bukan hanya ancaman terhadap Rusia, tetapi juga pukulan geopolitik ke negara-negara besar seperti India, Tiongkok, dan negara-negara berkembang lainnya yang menggantungkan pasokan energinya dari Rusia.
Trump menegaskan, “Jika saya pikir ini kesalahan Rusia… saya akan memberlakukan tarif sekunder pada semua minyak dari Rusia,” (Shalal, 2025). Lebih jauh, dia menyatakan bahwa perusahaan yang membeli minyak dari Rusia tidak boleh lagi melakukan bisnis di Amerika Serikat. Ucapan ini disampaikannya dengan nada emosi—bahkan dia mengaku "pissed off" atas komentar Vladimir Putin terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy.
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran luas. Dunia kini menghadapi bukan hanya konflik militer, tetapi juga potensi konflik dagang global berbasis energi. Dalam konteks ini, tarif sekunder menjadi senjata diplomatik yang menekan negara-negara mitra Rusia tanpa perlu menargetkan Rusia secara langsung.
Tarif Sekunder: Alat Tekanan atau Bumerang?
Di atas kertas, kebijakan ini tampak strategis: AS ingin menekan Rusia secara tidak langsung dan memaksa negara lain untuk meninggalkan pasokan energi dari Moskow. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini sangat problematik. Bagaimana AS akan memverifikasi bahwa sebuah negara membeli minyak Rusia? Apakah seluruh mitra dagang AS harus membuka data kontrak energinya? Bahkan William Reinsch dari Center for Strategic and International Studies mempertanyakan kejelasan teknis kebijakan ini (Shalal, 2025).
Lebih berbahaya lagi, kebijakan ini membuka babak baru dalam penggunaan hegemoni ekonomi AS untuk mengatur kebijakan luar negeri negara lain. Ini bukan lagi tentang memerangi Rusia, tetapi tentang mengendalikan pasar global lewat jalur energi.
Dilema Negara Berkembang
Bagi negara-negara berkembang seperti India, kebijakan ini menempatkan mereka dalam dilema. India telah menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia, mencapai 35% dari total impor minyaknya pada 2024 (Shalal, 2025). Mengapa? Karena minyak Rusia ditawarkan dengan harga diskon besar, sangat menguntungkan untuk menjaga inflasi dan stabilitas fiskal.
Jika India harus menghindari minyak Rusia demi menghindari tarif AS, maka harga energi dalam negeri akan naik drastis. Situasi yang sama bisa terjadi di banyak negara Global South. Negara-negara ini tertekan antara kebutuhan energi murah dan risiko kehilangan akses ke pasar AS.
Indonesia sendiri bukan pembeli langsung minyak Rusia dalam jumlah besar, tetapi sangat rentan terhadap dampak global. Lonjakan harga minyak akibat gejolak pasar dapat meningkatkan beban subsidi BBM, memperlemah nilai tukar rupiah, dan pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.
Dedollarisasi dan Fragmentasi Global
AS tidak inginkan dedollarisasi, namun langkah kebijakan Trump justru bisa mempercepat dedollarisasi. Kesempatan makin terbuka buat negara-negara seperti Tiongkok dan India untuk memperkuat sistem pembayaran alternatif. Sistem seperti CIPS atau penggunaan yuan dalam transaksi energi makin kuat untuk menghindari tekanan AS. Blok seperti BRICS bisa lebih solid karena merasa dipaksa untuk “memilih sisi”.
Kebijakan tariff Trump adalah untuk melemahkan posisi Rusia. Akibatnya dapat memicu fragmentasi sistem keuangan global. Tatanan global yang selama ini justru memberi AS pengaruh terbesar berpotensi rusak.
Bagaimana Indonesia Bersikap?
Indonesia perlu mengutamakan ketahanan energi nasional agar tidak mudah terguncang oleh gejolak pasar global. Di saat yang sama, diplomasi strategis harus diperkuat untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Pemerintah perlu mengambil langkah terintegrasi untuk menghadapi tekanan energi global dengan mengamankan pasokan dari berbagai mitra internasional sekaligus memperkuat cadangan nasional sebagai benteng ketahanan dalam jangka pendek. Di sisi lain, percepatan transisi menuju energi terbarukan harus menjadi prioritas strategis guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar minyak global yang rentan. Secara paralel, Indonesia juga harus aktif menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di forum G20 dan ASEAN, khususnya dalam menolak kebijakan sepihak yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia.
Kita juga harus memperkuat kerja sama bilateral dengan mitra-mitra energi seperti Arab Saudi, UEA, dan bahkan mitra regional seperti Malaysia. Selain itu, Indonesia bisa mendorong kerangka kerja multilateral yang melindungi kedaulatan energi dan hak negara untuk menentukan mitra dagangnya.
Penutup
Dunia saat ini tidak membutuhkan tekanan baru, melainkan pemulihan, kerja sama, dan kejelasan arah untuk keluar dari krisis berkelanjutan. Penggunaan tarif sekunder sebagai instrumen diplomatik tidak akan menyelesaikan konflik di Ukraina, melainkan berisiko menyebarkan instabilitas ke negara-negara yang tidak terlibat langsung. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan anggota aktif G20 memiliki posisi strategis untuk tampil sebagai penyeimbang di tengah lanskap global yang semakin terpolarisasi. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh tinggal diam ketika prinsip keadilan global dikalahkan oleh ambisi sepihak yang mengancam stabilitas dan tatanan internasional.
Referensi:
Shalal, A. (2025, March 31). 'Pissed off' at Putin, Trump threatens tariffs on Russian oil if Moscow blocks Ukraine deal. Reuters. Retrieved from https://www.reuters.com/world/us/donald-trump/
*Penulis: Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE. MA (Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)

 1 day ago
8
1 day ago
8