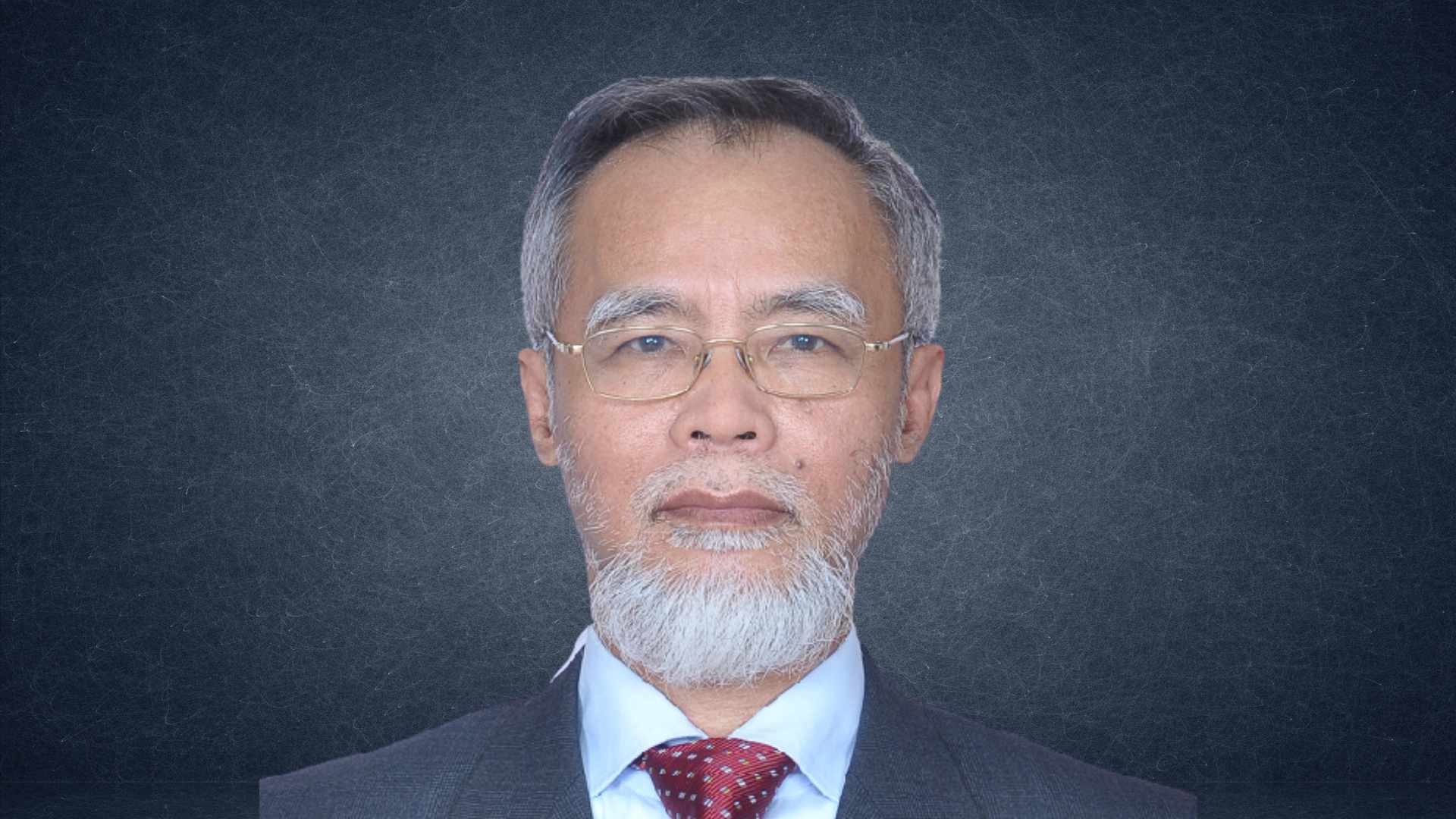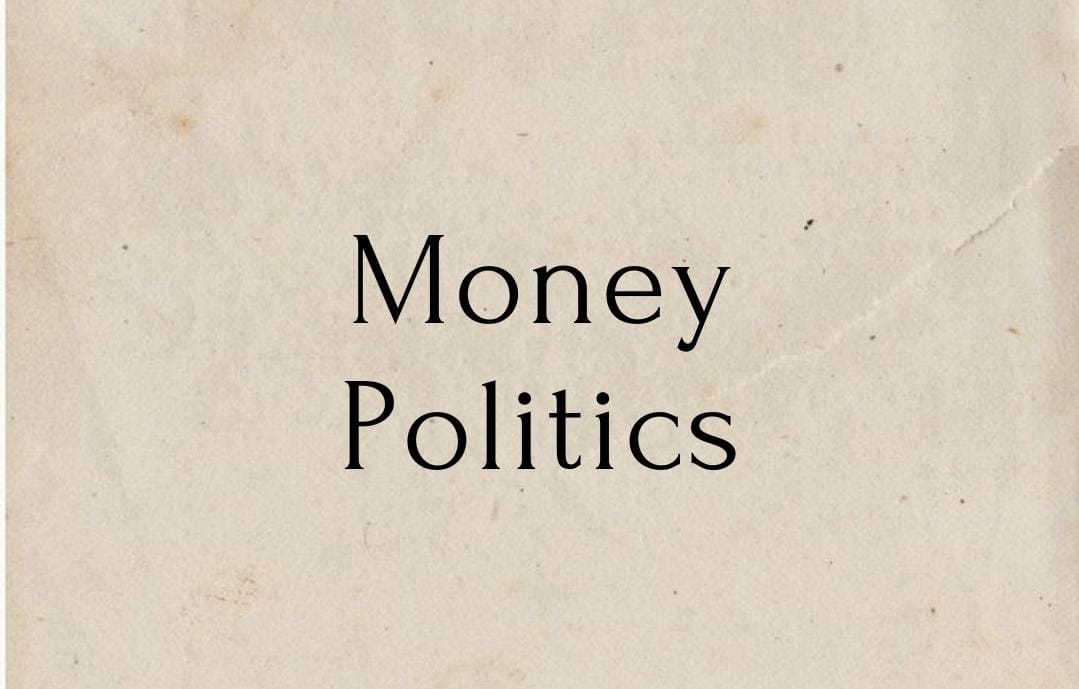Amerika Serikat tidak lagi memimpin dunia dengan idealisme demokrasi. Di era "America First", Negeri Paman Sam memosisikan dirinya sebagai negara dagang yang berpikir secara kalkulatif: siapa untung, siapa rugi. Jika negara mitra memberikan nilai tambah ekonomi, hubungan dilanjutkan. Jika tidak, AS siap mundur. Ini bukan sekadar slogan politik—ini strategi negara.
Perubahan wajah Amerika ini tampak jelas sejak kepemimpinan Donald Trump. Retorika tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan kerja sama multilateral digantikan oleh seruan “Bring jobs back to America” dan “Fair trade, not free trade.” Dengan tegas, Trump menyatakan bahwa AS tidak lagi akan menanggung beban dunia tanpa imbal balik. Ia memotong kontribusi ke PBB, menekan NATO untuk membayar lebih, dan me-restrukturisasi perjanjian dagang seperti NAFTA menjadi USMCA.
Namun, pendekatan ini bukan hanya milik Trump. Bahkan di bawah kepemimpinan Joe Biden, semangat "America First" tetap hidup dalam bentuk yang lebih halus. Pemerintah AS masih melindungi industri dalam negerinya, menjaga teknologi strategis dari ekspor ke Tiongkok, dan terus menekankan perlunya “resilience” dalam rantai pasok global. Dalam praktiknya, Amerika melihat dunia bukan sebagai komunitas nilai, tetapi sebagai arena pasar.
Strategi ini berpijak pada kalkulasi realistis: kekuatan ekonomi adalah fondasi kekuatan nasional. Negara yang kuat secara ekonomi bisa membiayai militer, mendominasi teknologi, dan memimpin diplomasi. Oleh karena itu, AS menuntut setiap hubungan bilateral untuk memberikan keuntungan ekonomi nyata. Tidak cukup sekadar menjadi sekutu; mitra harus memberikan nilai tambah yang terukur—baik sebagai pasar ekspor, lokasi investasi, atau sumber bahan mentah strategis.
Akibatnya, banyak negara—termasuk sekutu dekat AS—mulai merasa tekanan. Jerman dan Jepang, misalnya, dipaksa menaikkan anggaran pertahanan mereka agar tidak terus bergantung pada payung militer AS. Kanada dan Meksiko harus menyesuaikan ulang perjanjian dagang agar lebih menguntungkan AS. Bahkan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak lagi bisa mengandalkan retorika kemitraan strategis tanpa menunjukkan bukti ekonomi konkret.
Di satu sisi, strategi ini membuat AS tampil lebih transparan. Tidak ada lagi jargon normatif tentang “tatanan dunia berbasis aturan” yang hanya berlaku sepihak. Amerika berbicara dengan bahasa pasar: seberapa besar keuntungan, seberapa tinggi risikonya, dan seberapa relevan mitra tersebut bagi pertumbuhan ekonomi AS.
Namun di sisi lain, pendekatan ini juga menciptakan ketidakpastian global. Dengan mengabaikan multilateralisme, AS melemahkan banyak institusi global yang dulu ia bangun sendiri. Ketika AS menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris atau menghentikan pendanaan WHO, dunia kehilangan satu poros koordinasi global. Negara-negara menengah seperti Indonesia pun harus menavigasi relasi baru yang lebih kompleks dan penuh perhitungan.
Di tengah perubahan ini, Indonesia tidak boleh pasif. Kita harus membaca dengan jernih bahwa dunia kini bergerak dari idealisme ke pragmatisme. Hubungan luar negeri tidak cukup dibangun atas dasar sejarah dan simbol. Kita harus memperkuat diplomasi ekonomi, memperjelas posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik, dan menawarkan nilai konkret bagi mitra besar seperti AS, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa.
Indonesia memiliki banyak kartu yang bisa dimainkan: pasar besar, posisi geografis strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan populasi muda produktif. Namun semua itu hanya akan bernilai jika kita bisa mengemasnya dalam narasi kebijakan yang jelas dan berani. Jika kita ingin dihargai sebagai mitra sejajar, kita harus menawarkan manfaat yang dapat dihitung, bukan hanya retorika netralitas.
"America First" bukan sekadar politik dagang AS. Ia mencerminkan arus besar di dunia yang semakin kompetitif dan transaksional. Negara-negara tidak lagi bertanya, “Apa nilai kita bersama?”, melainkan “Apa yang bisa kamu tawarkan?” Dalam logika ini, setiap negara dituntut untuk membuktikan relevansi ekonominya atau siap tersingkir dari radar diplomatik negara-negara besar.
Karena itu, Indonesia perlu keluar dari zona nyaman diplomasi simbolik. Kita harus aktif membentuk aliansi yang didasarkan pada kepentingan nasional yang konkret. Kita perlu membangun daya tawar melalui kekuatan industri, ketahanan pangan, inovasi teknologi, dan integrasi kawasan. Dan yang terpenting, kita harus berani menyuarakan kepentingan sendiri, bukan sekadar mengikuti arus kekuatan besar.
Strategi "America First" mungkin membuat dunia menjadi lebih keras dan dingin. Tetapi ia juga membuka peluang bagi negara yang cerdas membaca arah angin. Dalam dunia yang dikendalikan oleh kepentingan ekonomi, yang dibutuhkan bukan sekadar teman, melainkan mitra yang kuat dan relevan. Dan Indonesia bisa menjadi salah satunya—asal kita berani bermain di panggung global dengan cara yang baru.
*Penulis: Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE. MA (Dosen Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)

 3 days ago
10
3 days ago
10